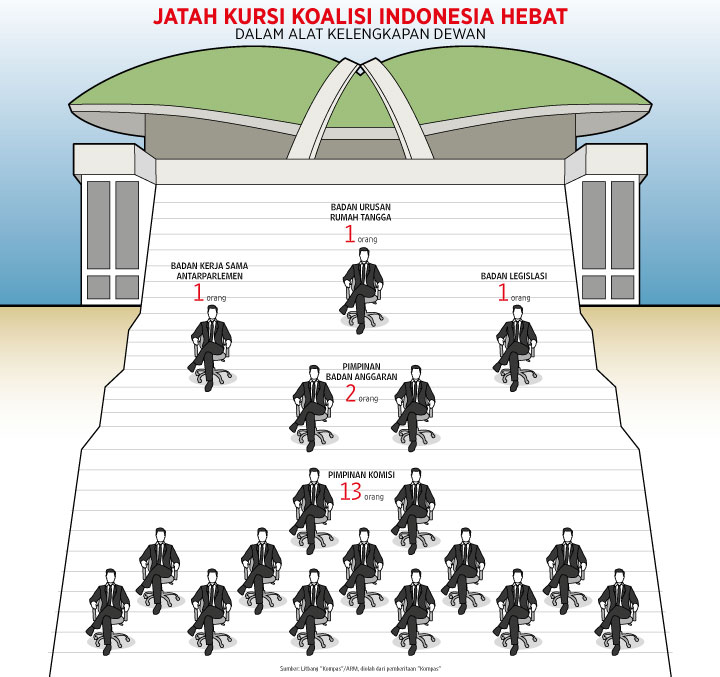PRESIDEN pertama RI Soekarno dalam bukunya, Mencapai Indonesia Merdeka, pernah berkata, ”Partailah yang memegang obor, partailah yang berjalan di muka, partailah yang menyuluhi jalan yang gelap dan penuh dengan ranjau-ranjau sehingga menjadi jalan terang.”
Mengacu pada kondisi perpolitikan kini, cita-cita Soekarno itu terasa utopis. Bagaimana mau menerangi jalan dan berfungsi sebagai sarana pengatur konflik apabila parpol kini dirundung awan gelap? Itulah kondisi dua partai legendaris Indonesia, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang selama beberapa bulan terakhir ini terpecah.
Perebutan kursi ketua umum partai berujung pada kepengurusan ganda. Kalangan elite, kader, sampai tokoh senior, terbelah menjadi kubu-kubu yang terpisah. Kantor kepengurusan pusat diperebutkan. Perundingan untuk mencapai islah (perdamaian) belum mencapai titik temu sepenuhnya.
Padahal, harga yang dibayar tidak main-main. Selain kehilangan wibawa di hadapan publik, kader partai di daerah terancam tidak bisa mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah tahun ini. Ketua DPP Golkar versi Munas Ancol Leo Nababan bahkan mengibaratkan partainya seperti dinosaurus. ”Eksistensi Golkar hanya dimaknai sebagai pernah ada (di pilkada sebelumnya), tetapi (kini) tidak ada lagi,” katanya, dalam suatu perbincangan santai.
Di sisi lain, konflik partai yang berkepanjangan dikhawatirkan akan memengaruhi kinerja fraksi-fraksi di parlemen, yang Senin (12/1) ini akan memasuki masa sidang ketiga.
Situasi bangsa ke depan juga penuh dengan tantangan. Salah satunya, Pasar Terbuka ASEAN yang bergulir 2015. Negara membutuhkan parpol yang kokoh, yang bisa menopang negara di tengah tantangan.
Lagu lamaSebenarnya, fenomena perpecahan parpol bukan barang baru. Polarisasi dalam tubuh partai telah terjadi berulang kali sepanjang sejarah perpolitikan Indonesia.
Partai Nasional Indonesia (PNI) pernah mengalami konflik yang dipicu pertanyaan sejumlah anggotanya yang lebih ”radikal” terkait komitmen pengabdian PNI terhadap persoalan rakyat. Mereka menilai, pemimpin PNI saat itu terlalu kompromistis. Tidak setuju dengan pergerakan partai yang menjauh dari cita-cita awal, mereka lalu keluar dari PNI.
Perpecahan juga pernah menimpa Sarekat Islam (SI) pada sekitar 1920. Dualisme saat itu terjadi akibat ketidaksamaan pandangan anggota mengenai dasar ideologi dan perjuangan partai, yang terpecah antara paham komunisme dan Islam.
Masing-masing pihak berkukuh dengan keyakinan ideologinya hingga menimbulkan friksi. SI Semarang yang mengusung paham komunisme pada akhirnya bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sementara kelompok dengan ideologi Islam tetap bertahan di Central Sarekat Islam (CSI).
Meski telah terjadi sebelumnya, ada perbedaan yang signifikan antara konflik parpol dulu dan sekarang. Dulu, konflik muncul akibat adanya perbedaan pandang tentang gagasan besar partai. Sekarang, gesekan di internal partai mengerdil menjadi sebatas perebutan kursi kekuasaan. Ideologi dan cita-cita penentu arah pergerakan parpol sebagai pilar demokrasi malah semakin dilupakan.
Munculnya kepengurusan ganda di Partai Golkar, misalnya, dimulai perebutan kursi kepemimpinan partai antara golongan muda dan tua. Golongan muda Golkar, diwakili Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Airlangga Hartarto, dan lain-lain, mencalonkan diri sebagai ketua umum dalam Munas IX Golkar.
Mereka menginginkan adanya regenerasi yang demokratis di tubuh partai berlambang pohon beringin itu. Akan tetapi, dengan skenario aklamasi, Ketua Umum (petahana) Aburizal Bakrie yang dianggap mewakili golongan tua terpilih lagi sebagai Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas IX di Bali.
Tidak puas, para kader muda menggelar munas tandingan di Ancol, Jakarta, yang menghasilkan kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Agung Laksono. Golkar pun terpecah menjadi dua. Perpecahan itu bahkan dibawa sampai ke parlemen demi menegaskan eksistensi kekuasaan masing-masing kubu. Mengutip Ketua DPP Golkar versi Munas Ancol Melchias Mekeng, ”DPP sana (kubu Ical) punya fraksi di DPR. DPP kami (kubu Agung) juga harus punya.”
Fungsionaris Partai Golkar, Hajriyanto Thohari, ikut menyindir perpecahan yang terjadi di partainya. Konflik di Partai Golkar saat ini hanya seputar perebutan jabatan yang sama sekali tidak berdimensi ideologis. ”Konflik muncul semata-mata karena ambisi kekuasaan dan saling berebut jabatan politik di internal partai. Mereka bahkan tidak sadar, tindakan mereka bisa membuat Golkar lebih terpuruk pada Pemilu 2019,” kata Hajriyanto.
Egoisme demi mempertahankan jabatan dan kekuasaan juga terlihat di tubuh PPP. Proses islah belum mencapai titik temu karena masing-masing kubu merasa memiliki legalitas.
Merger dan pembagian kursi kepengurusan secara proporsional di luar munas atau muktamar tidak mudah. Peneliti Riset Pusat Pengkajian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, tiap elite partai berkepentingan untuk mempertahankan jabatan dan kekuasaannya. Hal itu berpotensi menuju kebuntuan.
Tak dapat dimungkiri, parpol tak cuma kehilangan wibawa di mata publik, tetapi juga kehilangan roh sebagai organisasi sosial-politik. Upaya lebih dari elite parpol untuk membuang ego dan rasa haus kekuasaan amat diwajibkan. Hanya dengan demikianlah, parpol kembali pada roh dan cita-citanya: menjadi penerang bagi perjalanan bangsa yang gelap dan penuh ranjau. (AGNES THEODORA WAGUNU)